Cinta Indhira, Rasa Yang Tak Hanya
Novel
Karya Athfah Dewi
Bab 7. Bukti Cinta
__________
“Sama bapak dari anak yang sedang kamu kandung itu.”
“Siapa? Dan dari mana Papa tahu kalau dia pelakunya?”
“Dia bilang sendiri sama papa. Dia mengakui semuanya.”
“Siapa, Pa?”
“Kenapa tanya sama papa? Tanya saja langsung sama orangnya.”
“Gimana mau tanya orangnya, aku aja gak tahu.”
“Sudahlah Indhira, kamu itu jangan bikin papa pusing. Besok, kamu tinggal siap-siap. Papa belum hubungin Mbah Uti. Ditelepon belum diangkat.”
“Pa. Siapapun orangnya. Aku gak mau nikah sama dia.”
“Kamu ini apa-apaan? Sudah! Jangan bikin masalah lagi!” Sambungan teleponnya pun langsung terputus.
“Pa!”
Aku duduk di bangku dengan kesal. Pecuma berteriak sekencang apapun juga, sebab Papa tidak akan pernah mendengarkanku.
Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menikah dengan Laki-laki yang tidak aku cintai. Meski katanya dia yang sudah membuat aku harus mengandung anak ini.
Bagaimana dengan perasaanku? Aku tidak menginginkan sebuah pernikahan. Lagipula, menikah bukan solusi. Justru, akan kuhajar laki-laki itu jika berani menampakkan wajahnya di depanku.
Aku terus menunduk, meremas kepala frustasi. Baru juga merasa tenang tinggal di sini, ada saja yang mengusik.
Aku berdiri, tiba-tiba mataku menangkap sebuah bayangan di balik pohon di pinggir sawah. “Hey! Siapa itu?” tanyaku sambil mendekat.
Tidak ada jawaban. Aku menghentikan langkah. Apa itu binatang?
Aku berjongkok mencari sebuah batu, lalu kuangkat ke atas bersiap-siap untuk melemparkannya ke arah pohon yang masih bergoyang.
Satu … dua … ti ….
“Mbak, ini saya. Jangan lempar!” seru seseorang sambil keluar dari sana.
“Rahman? Ngapain di sana? Ngintip, ya?” tanyaku sambil menatapnya tajam.
“Enggak, gak ngintip. Saya lewat, terus terpeleset,” jawabnya.
Aku melirik ke bawah. Ternyata iya, kaki kanan Rahman kotor penuh lumpur. “Awas kalau ngintip!” ancamku sambil berlalu ke dalam.
“Enggaklah. Ngapain ngintip orang teleponan sambil marah-marah,” ucap Rahman agak pelan.
Namun, aku masih bisa mendengarnya dengan jelas. Karena suasana hati yang sedang kacau, aku pun tidak menghiraukannya.
Aku terus melangkah, berniat untuk masuk rumah. Sebentar … aku berhenti. Rahman tahu aku teleponan sambil marah-marah, berarti dia mendengarkanku tadi! Aku membalikkan tubuh. “Rahmaan!”
Orang yang aku panggil, tidak melirikku sedikit pun. Dia terus berjalan dengan cepat.
Kenapa aku khawatir Rahman tahu kalau Appa mau menikahkanku? Lagipula, bukankah dia juga tahu cerita bohong yang Mbah Uti sebarkan, bahwa aku sudah menikah dan suamiku di luar negeri?
Ya, waktu di bazaar itu, dan sejak saat itu Rahman berubah sikap. Sepertinya, dia percaya cerita tersebut.
Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya dada ini terasa teramat sesak. Benar sekali, mana mungkin Rahman mau dekat dengan perempuan bersuami. Atau, kalaupun dia tahu cerita sebenarnya. Tidak mungkin juga dia mau dekat denganku.
Ya, sekarang aku hanya seorang perempuan tidak berharga. Hamil tanpa suami. Bahkan, tanpa tahu siapa laki-laki yang sudah melakukan ini.
Aku jadi merasa tidak sabar, ingin segera esok hari. Akan kuhajar b******n itu!
“Dhira ….” Mbah Uti mendekatiku.
“Ya, Mbah.” Aku melirik ke arahnya sambil mengusap sudut mata.
“Barusan papamu telepon.”
Aku mengangguk. “Aku gak mau menikah dengan siapapun sekarang, Mbah. Bagaimana bisa, aku harus bersama laki-laki b******n itu?”
“Terus, apa rencana kamu besok?”
“Aku akan menolak. Tapi, kalau papa marah, apa Mbah akan belain aku?” Kutatap perempuan yang rambutnya sudah mulai memutih itu dengan penuh harapan.
“Insya Allah, mbah akan dukung kamu.”
“Makasih, ya, Mbah.” Aku langsung memeluknya.
Mbah Uti mengangguk, sambil mengusap punggungku.
“Kalau sampai papa gak mau biayain aku lagi. Aku mau kerja. Kerja apa aja, bantuin Mbah di kebun juga mau.”
“Gak mungkin papamu kaya gitu. Kamu ini, anak kesayangannya.”
“Kesayangan apaan? Nyatanya, dia malah bawa perempuan lain ke rumah. Ngegantiin posisi mama. Padahal aku udah mohon-mohon, supaya papa gak ngelakuin itu. Eh, gak peduli. Sampai aku harus menderita begini.”
“Niat papamu baik, ingin kamu tetap memiliki ibu.”
“Mama gak akan pernah tergantikan oleh siapapun, Mbah.”
“Mbah ngerti. Bukan untuk menggantikan, cuma untuk mengisi kekosongan di hidup kalian. Mama kamu, ya, mama kamu. Rossi, dia itu ibu sambung.”
“Apapun namanya, bagiku tetep sama. Aku, gak akan pernah bisa nerima perempuan lain.”
“Kamu, sayang banget sama almarhumah mama?” Mbah Uti menatapku.
“Tentu saja. Aku sayang banget sama mama. Makanya merasa sangat kehilangan dan gak mau ada orang yang gantiin posisinya.”
“Bukti cinta kamu sama almarhumah, apa?’
“Bukti cinta?” Aku melirik kepada Mbah Uti. Sepertinya, dia belum paham apa yang aku sampaikan baru saja.
“Iya. Kamu sayang sama mama kamu. Buktinya apa?”
“Kalau dulu waktu dia masih ada, aku sering memberinya hadiah. Memeluknya, menciumnya dan bilang kalau aku sayang banget sama mama. Selain itu, aku selalu berusaha jadi anak yang baik, biar hatinya senang.”
“Kalau sekarang?”
“Karena sekarang mama sudah gak ada, aku cuma bisa simpen kenangan manis kami dalam hati. Dan menjaganya dengan baik. Bukan hanya untuk diriku sendiri. Tapi, untuk papa juga. Makanya, aku gak mau papa nikah lagi. Karena, itu berarti papa sudah gak sayang dan cinta lagi sama mama. Harusnya, papa tetep nyimpen kenangan itu dalam hatinya. Tapi ….” Aku menghentikan kalimatku. Tenggorokan ini rasanya tercekat.
Mbah Uti mengusap punggungku.
“Tapi papa lebih milih perempuan itu. Bahkan, sampai mengabaikan aku, Mbah. Hati aku sakit ….” Tangisku pecah.
Mbah Uti memelukku. “Jangan sedih lagi. Sekarang, kan ada mbah yang akan nemenin kamu, ya?”
Aku mengangguk. Ya, sekarang aku tidak terlalu khawatir lagi. Karena, ada orang lain yang akan selalu menemaniku.
“Dan, untuk membuktikan kalau kamu sayang sama mama, kamu bisa mendoakannya.”
“Berdoa?”
“Ya, doa anak soleh, Insya Allah akan Allah dengar. Sebab, doa anak soleh dan solehah itu salah satu dari tiga amalan yang pahalanya tidak akan pernah terputus meski kita sudah meninggal.”
“Sepertinya, aku pernah denger tentang hal itu.”
“Lakukanlah, karena hanya itu bukti nyata rasa sayangmu buat almarhumah.”
Aku terdiam. Selama ini, aku memang jarang mendoakan mama. Selesai shalat pun, biasanya cepat-cepat membereskan mukena.
Aku terlalu sibuk meratapi nasib diri yang tidak bisa lagi memeluknya. Meratapi rasa sakit karena Papa yang sudah berpaling.
“Tapi, aku bukan anak yang solehah, Mbah.”
“Mulai sekarang, berusaha buat jadi anak yang solehah.”
***
Malam itu, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Memikirkan semua yang Mbah Uti katakan, dan menerka-nerka hal apa yang akan terjadi besok. Juga merasa penasaran siapa laki-laki kurang ajar itu, yang sudah menyeretku sampai di situasi rumit seperti ini.
Ketika terbangun pagi hari, tubuhku terasa agak lemas. Mbah Uti mengusulkan untuk mengunjungi bidan desa. Namun, aku menolaknya.
“Minta obatnya saja, ya? Biar minta tolong Rahman.”
Aku tidak mengiyakan atau melarang. Mendengar nama Rahman disebut, hatiku senang tetapi juga sedih.
Ternyata, obat yang aku perlukan di bidan desa sedang kosong, sehingga katanya dia pergi ke apotik di dekat pasar.
“Kamu sudah bersiap-siap?” tanya Mbah Uti.
“Bersiap-siap untuk apa, Mbah?” Aku balik bertanya.
“Kata papamu, dia mau ajak kamu pergi.”
Aku menggeleng. “Aku gak mau ke mana-mana. Mau di sini aja sama Mbah.”
“Ya sudah kalau begitu. Tapi, apapun yang papa kamu katakan, kamu jangan emosi dulu. Mbah gak mau kalian bertengkar.”
“Kalau papa yang mulai?”
“Kamu ngalah. Kamu tetep gak boleh meninggikan suara kepada orang tua.”
“Masa begitu? Yang salah mah tetep salah, Mbah. Gak boleh dibilang bener.”
“Bukan membenarkan, tapi kamu jangan ikut-ikutan berbuat salah. Orang tua itu, bagaimanapun dia, tetep harus dihormati.”
“Tapi, Mbah jangan lupa, buat dukung aku terus.”
“Insya Allah … asal kamu dengerin kata-kata mbah.” Mbah Uti melirik ke pintu depan. “Rahman mana, ya? Kenapa belum sampai juga?”
Aku pun melirik ke arah yang sedang Mbah Uti lihat.
“Kamu sekarang bagaimana, masih lemes?” Mbah Uti melirikku.
“Masih, Mbah.”
“Sarapannya habisin, biar nanti Rahman datang, bisa langsung minum obat.”
Aku mengangguk, meski terasa enggan untuk menghabiskan bubur yang Mbah Uti buat sendiri tadi.
Pukul tujuh, tiba-tiba terdengar suara mobil mendekat. Siapa dia? Tidak mungkin Rahman, karena dia mengendarai sepeda motor.
“Papamu sudah datang, Dhira …,” seru Mbah Uti.
Papa? Sepagi ini sudah sampai? Aku berdiri dan mengintip dari jendela. Benar saja, mobil Papa sudah terparkir di halaman dan dia pun tampak baru saja turun.
Aku menatapnya. Sebenarnya, aku sangat rindu. Ingin sekali memeluknya, seperti dulu kalau dia baru pulang dari luar kota.
Namun, begitu melihat istrinya. Rasa rindu itu memudar seketika. Aku duduk di sisi tempat tidur. Tidak ada keinginan untuk menyambutnya.
“Indhira … papamu sudah sampai,” teriak Mbah Uti.
Aku mengabaikannya. Hingga beberapa menit kemudian, terdengar pintu diketuk, lalu terbuka.
“Kamu sudah siap?” tanya Papa.
Lihat, dia pun seperti itu. Hampir dua bulan tidak bertemu, tidak terlihat rasa rindu sedikitpun darinya. Tidak ada pelukan apalagi ciuman. Atau, hanya sekadar menanyakan kondisiku.
“Aku gak akan kemana-mana,” jawabku sambil memalingkan muka.
“Indhira! Maksud kamu apa?”
“Kurang jelas? Aku gak akan kemana-mana!” seruku sambil membalas tatapannya.
Mbah Uti mendekat dan memegang lenganku.
“Kamu ikut sekarang!” bentak Papa. “Mbah, maaf … tolong kasih dia pengertian.”
“Jangan libatkan orang lain. Aku gak mau ke mana-mana!” seruku. Lalu, melepaskan pegangan Mbah dan berlari ke arah dapur.
“Indhira! Kamu jangan bikin masalah lagi!”Terdengar suara Papa berteriak, tetapi aku tidak menghiraukannya.
“Kamu harus menikah. Untuk menutupi aib yang kamu corengkan di muka papa, Indhira!”
“Aku gak mau nikah sama siapapun! Saat ini, aku gak butuh itu! Lagian, kalau sekarang ketemu b******n itu, akan aku habisi dia!” seruku sekuat tenaga sampai-sampai kedua mataku terpejam.
Lalu, aku mencoba mengatur napas yang masih terengah-engah karena emosi, kemudian membuka kedua mata perlahan.
Betapa terkejutnya aku, karena di pintu belakang ada Rahman yang sedang berdiri sambil menatapku.
“Rahman?”
“Ma-maaf, Mbak. Saya lewat pintu belakang karena di depan ada tamu,” ucapnya agak tergagap.
Beberapa saat, aku hanya terdiam dengan tidak melepaskan tatapan darinya. Apakah Rahman mendengar apa yang aku katakan tadi?
“Ini obatnya, Mbak.” Rahman memberikan sebuah kantong plastik.
Aku sudah mengulurkan tangan untuk mengambil itu. Namun, urung. Sebab, seseorang terdengar menyebut namaku.
“Indhira ….”
Aku membalikkan tubuh. Tampak Dhimas ada di sana. Wajahnya tampak lebam di mana-mana. Sudut bibir yang masih terdapat darah kering dan pipi kanan yang membiru dan bengkak.
Kenapa dia berada di sini dengan kondisi seperti itu? Bersambung (Insya Allah).

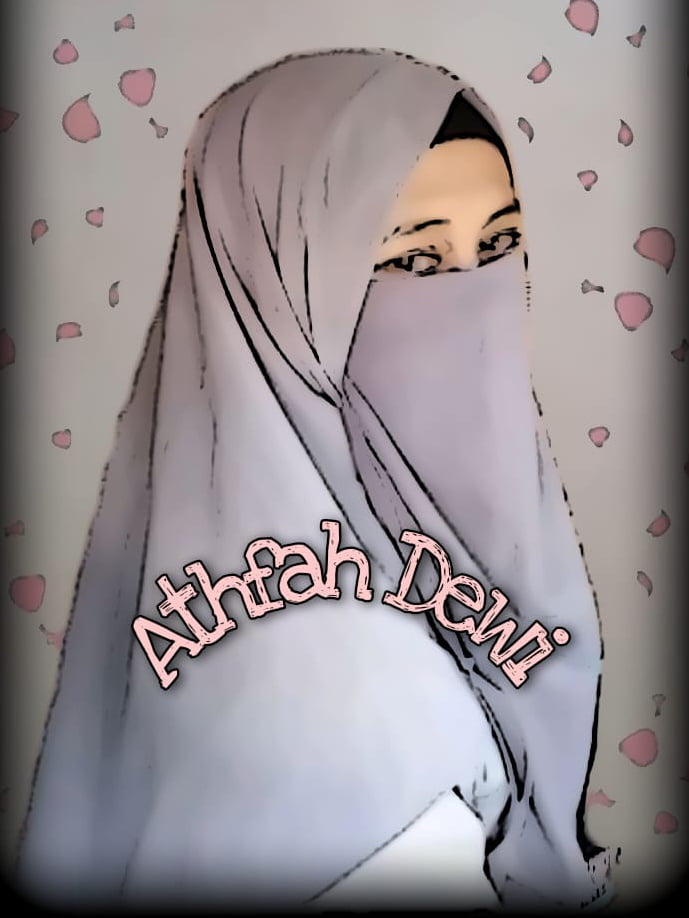






Comment